Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku lalu menjadi musuhmu?
– Prof. Jacob Elfinus Sahetapy.
Entah ada hubungannya atau tidak, setelah kesekian kalinya saya mendengar perkataan Prof. J.E. Sahetapy di atas, saya jadi tiba-tiba ingat tentang guru. Mungkin karena saya terlanjur menganggap beliau ini sebagai panutan, walaupun saya tidak pernah diajari oleh beliau; ketemu pun tidak pernah. Saya teringat, dulu selama sekolah, siapa ya guru yang ajarannya membekas pada saya? Setelah saya ingat-ingat ternyata hanya ada satu orang guru yang seperti itu, dan mungkin ini menyedihkan, tetapi ternyata guru itu bukan guru agama.
Beliau guru SD saya sejak kelas 4 hingga kelas 6. Namanya pak Abdul Rahman, mengajar Matematika, Bahasa Indonesia dan IPS di SD Hikmah I YAPIS Jayapura Utara hingga tahun 1992. Apa yang membekas? Beliau mengajarkan bahwa orang harus berusaha tahu banyak hal, bukan saja satu-dua bidang. “Jadi orang jangan otak tempe,” katanya. Hampir setiap hari, kalau beliau kebagian mengajar jam pelajaran terakhir, beliau tidak mau membiarkan kami pulang begitu saja. Ada sayembara ilmu pengetahuan umum – ibukota negara anu, nama danau di kota anu, dan sebagainya – dan hanya yang menjawab benar yang boleh pulang. Itu membekas sekali. Pertama kalinya kami paham, ternyata belajar itu bukan cuma untuk ujian saja.
Lho kok itu doang? Urusan moral bagaimana?
Setelah saya ingat-ingat ternyata tidak ada guru yang ajaran moralnya membekas pada saya. Yang terjadi, saya hanya dihadapkan pada satu pertentangan yang satu ke pertentangan yang lain, dari apa yang diajarkan dengan apa yang saya lihat di sekeliling saya. Saya belajar bahwa yang menurut buku-buku dan mulut guru-guru disebut “baik” itu ternyata selalu kalah. Hidup mengajarkan bahwa orang harus kuat. Walaupun tidak sesuai buku, kalau kuat niscaya menang, niscaya menjadi hebat. Semestinya kalau menuruti ajaran sang hidup, saya bakal tumbuh dewasa sebagai manusia busuk yang haus kekuatan dan kekuasaan. Syukurlah entah dari mana saya diwarisi karakter keras kepala. Selalu ingin menentang. Menentang membabi buta. Semakin deras kekuatan yang mendorong saya ke kanan, saya akan berusaha belok kiri. Demikian sebaliknya. Syukurlah lagi, kekuatan yang dominan bercokol di sekeliling saya sejak orok hingga paruh baya adalah kekuatan jahat. Negara jahat yang diatur penguasa jahat dengan rakyat jahat di dalam naungan masyarakat jahat yang menganut nilai-nilai sosial yang jahat yang mengajarkan ilmu-ilmu jahat. Syukurlah, dengan demikian saya berusaha jadi orang baik. Atau orang apa sajalah, yang penting bukan orang jahat. Orang yang seperti di buku. Maka, sesungguhnya yang mengajarkan moral kepada saya adalah semesta. Katanya semesta itu media Allah, jadi konon sesungguhnya Allah SWT-lah yang mengajarkan moral kepada saya.
Sepertinya sudah lebih dari satu kali saya menyebut kata “syukurlah” di atas. Jadi mungkin saat ini saya sedang bersyukur. Alhamdulillah. Syukurlah walaupun saya jarang sekali sholat, saya tidak jadi seperti bajingan-bajingan yang sering disebut Prof. J.E. Sahetapy sebagai “bajingan” itu. Saya tidak maling, saya tidak korupsi, saya tidak terima sogok.
Ah sebentar. Setelah saya ingat-ingat lagi, saya sebenarnya pernah korupsi, dan pernah juga terima sogok. Kalau tidak salah waktu itu saya kepepet™. Saya masih ingat jumlah uangnya. Korupsi satu kali saat masih jadi mahasiswa, dalam kepanitiaan kegiatan apa-itu-saya-tidak-ingat-lagi, besarannya 500 ribu. Lalu korupsi satu kali lagi saat sudah jadi dosen, jumlahnya 3 juta. Sebelumnya pernah terima sogok satu kali, jumlahnya 300 ribu. Jadi total saya sudah makan uang haram sebesar 3.800.000 rupiah. Eh sebentar, tidak semua dimakan. Yang 500 ribu saat kuliah itu saya belikan sepatu 385 ribu. Sepatunya tidak saya makan. Haram hukumnya makan sepatu. Jadi total isi perut saya dari uang haram hingga saat ini adalah 3.415.000 rupiah. Saya tidak tahu cara mengembalikan uang itu bagaimana. Kalau saya kembalikan ke lembaga tempat saya bekerja, menurut nasihat orang terdekat itu cuma cari perkara saja, yang ada malah banyak orang yang bakal tersinggung karena dikiranya saya menyindir mereka yang korupsi puluhan juta tapi tidak ada niat mengembalikan. Akhirnya saya putuskan, uang itu saya anggap milik Allah SWT, sehingga biarlah saya kembalikan kepada-Nya saja. Caranya, ya lewat perantara Beliau, yaitu lewat hamba-Nya yang membutuhkan. Kalau bahasa kerennya, saya kembalikan lewat sedekah. Bah sedekah kok ngomong, jadi ndak ikhlas dong. Sebenarnya ini lebih layak disebut bayar hutang, bukan sedekah; bayar hutang kepada Allah SWT, jadi disebut tidak ikhlas pun tidak masalah. Tentang sudah terbayar lunas atau belum itu uang 3 jutaan yang saya korupsi, wallahua’lam. Wong saya juga ndak pernah ngitung. Untuk amannya dianggap belum lunas saja lah, supaya saya merasa berhutang terus sama Allah. Itu konon katanya lebih baik buat saya jika saya berpikir.
Tadi sampai di mana? Oh ya, tentang pencitraan bahwasanya saya tidak korupsi. Mungkin perlu ditambah : saya tidak “hobi” korupsi. Seperti alesyan™ yang sudah saya ungkapkan tadi, saya korupsi karena kepepet™. Jadi walaupun saya pernah korupsi, saya bukan koruptor; karena korupsi yang saya lakukan itu bukan profesi, hobi pun bukan. Jadi jelas ya, saya orang baik lho. Catat.
Nah. Dalam kapasitas saya sebagai orang baik™ ini, saya ingin berkontemplasi mengenai guru. Saya ini sekarang pendidik. Karena inspirasi utama yang saya dapatkan dari pendidikan saya adalah dari pak guru SD yang saya sebut di awal tadi, otomatis muatan ajaran saya, cara mengajar saya kepada mahasiswa, adalah tidak jauh-jauh dari pendewaan logika. Saya ingin manusia didikan saya tidak berpikir hal lain selain bagaimana mengisi otaknya dengan ilmu. Bagaimana supaya pintar. Lalu bagaimana soal moral? Saya berpandangan, lebih mudah mengajarkan moral kepada orang yang pintar daripada kepada orang bodoh. Mengapa? Karena orang yang pintar sudah mampu memilah-milah pengaruh. Orang yang pintar tidak dapat dipengaruhi; melainkan dialah yang mengijinkan pengaruh masuk kepadanya, setelah menyeleksi dampak pengaruh itu dengan logika yang waras. Berbeda dengan orang bodoh. Sekarang diajari moral, besok dia belajar barang baru lagi, menemui kenyataan lain lagi yang tidak sesuai dengan moral yang dipelajari hari ini, lalu dengan segala kekurangannya dia menimbang-nimbang, dan akhirnya memutuskan moral itu tidak layak dipakai lagi. Orang bodoh terlalu gampang dipengaruhi. Jadi, kasih pintar dulu, baru kasih tau moral yang baik itu bagaimana.
Jadi, apakah saya menentang pengajaran moral kepada anak usia dini? Tidak juga. Terserah saja kapan atau seberapa sering mengajarkan moral. Tetapi sebaiknya jangan menganggap moral lebih penting daripada logika. Soalnya logika itu instrumen yang penting untuk menelaah pengaruh. Jatuh-bangun-jatuhnya bangsa ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak punya daya apa-apa di hadapan sang pengaruh. Sudah terlalu kenyang orang melihat betapa agama sudah dijadikan topeng saja, alat yang dipakai orang-orang jahat untuk mendapat pengakuan dan restu untuk terus melakukan hal-hal jahat. Pengakuan dan restu dari orang-orang bodoh, yang pandangannya tidak sanggup menembus topeng agama. Ini kan masalah.
Selama ini tidak gampang saya menanamkan ajaran tentang akal sehat, tentang logika tadi. Apalagi lembaga tempat saya mengajar ini platformnya agama. Sering mahasiswa saya terang-terangan bilang, “Buat apa dengar orang yang tidak sholat!”, yang mana saya cuma bisa cengar-cengir saja. Saya tidak bisa pakai argumentatum ad hominem untuk menanggapi pandangan itu. Saya tidak bisa bilang, “Jangan lihat orangnya, lihatlah apa yang dia sampaikan”; tidak bisa, selama saya masih terus menuntut kaum pembela agama untuk menunjukkan teladan. Selama saya masih mengutuki mereka yang sikap dan tindak-tanduknya tidak mencerminkan mulutnya. Kan mereka juga bisa bilang ad hominem? Saya hanya bisa bilang, teladan saya hingga sekarang ini cuma mampu segini saja. Kalau berkenan, mohon telaah baik-baik sebelum menuding bahwa orang yang jarang sholat itu pasti ndak bener. Karena faktanya terlalu banyak contoh orang yang rajin sholat tetapi ternyata sholatnya itu tidak membuat dia nahi munkar. Amar ma’ruf, mengajak pada kebaikan, iya; tapi sambil mendirikan munkar. Tapi itu tentu perkara lain. Toh masih bisa dijawab lagi dengan argumen “Rajin sholat saja masih bejat, apalagi kalo jarang sholat!”.
Yang mau saya bilang, mengajar itu susah. Jadi pendidik itu susah. Saya merasa punya ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia yang layak untuk diwariskan, yang tidak kalah layaknya dengan ilmu akhirat. Tetapi agar ilmu saya itu diterima, ternyata saya juga harus menunjukkan teladan dalam ilmu akhirat. Saya dituntut untuk menjadi lebih dari yang saya mampu. Tapi ya tidak apa-apa, toh tidak semua didikan saya seperti yang saya sebut tadi. Masih ada yang matanya mampu menangkap yang baik-baik dari segala yang saya ocehkan. Alhamdulillah. Paling tidak saya masih bisa merasa bermanfaat.
Ya sudah. Tidak ada kesimpulan. Segini saja.
Assalamu’alaikum warohmatullahi wa barokatuh.
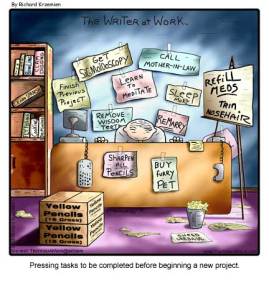











Recent Comments